Kampus adalah dermaga, sebagian mahasiswa hanya singgah sebentar, sekadar menambatkan perahu lalu berlayar lagi tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Tetapi ada pula yang menjadikannya samudra—mengayuh jauh, menantang ombak, dan menemukan pulau-pulau hikmah yang tak tertulis di silabus.
Jika engkau hanya duduk manis di kelas, mencatat seperlunya, dan pulang dengan selimut malas, maka kelak engkau hanya pulang membawa selembar ijazah. Dunia tidak menunggu gelarmu, dunia menunggu keberanianmu. Dan keberanian itu tumbuh di luar jam kuliah—di ruang diskusi yang riuh, di rapat organisasi yang melelahkan, di jalanan yang berdebu saat idealisme diuji.

Saya teringat pesan Pramoedya Ananta Toer: “Didiklah rakyat dengan organisasi, dan didiklah diri dalam perlawanan.” Kutipan ini bukan sekadar seruan, tetapi arah mata angin pendidikan tinggi. Mahasiswa yang tangguh secara akademik akan menjadi matang bila ditempa dalam organisasi, karena di sanalah mereka belajar mengelola konflik, menyusun strategi, membangun jejaring, dan mengambil keputusan. Kampus mengajarkan teori, tapi organisasi mengajarkan realitas yang tak tertulis di buku ajar. Seperti pepatah Arab, “Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.” Pengetahuan yang tak pernah diujikan di kehidupan nyata hanya akan menjadi debu di rak perpustakaan.
Hasyim Asy’ari pernah mengingatkan bahwa menuntut ilmu adalah perjalanan yang harus disertai adab dan perjuangan. Dalam organisasi, mahasiswa belajar menghormati proses, menghargai perbedaan, dan memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar titel. Buya Hamka pun berkata, “Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera pun bekerja.” Maka menjadi mahasiswa tak cukup hanya datang, duduk, dan pulang. Ia adalah perjalanan untuk menemukan makna.
Di tengah tuntutan akademik yang menjerat, saya melihat mahasiswa yang berani memikul beban ganda: menuntaskan skripsi sambil memimpin aksi, mengerjakan tugas sambil mengelola gerakan sosial, belajar untuk ujian sambil mengajar anak-anak di desa. Mereka membuktikan bahwa ruang kuliah hanyalah satu sisi dari pendidikan. Tan Malaka pernah berkata, berpikir kritis memerlukan keberanian untuk meragukan, bahkan menentang, bila kenyataan tak selaras dengan kebenaran. Sikap seperti inilah yang perlu dijaga agar kampus tidak menjadi ruang sunyi yang membungkam pikiran.
Tugas kita sebagai pendidik bukan sekadar mengisi kepala mahasiswa, melainkan menyalakan obor di tangannya agar ia mampu menapaki jalan yang gelap, berliku, bahkan penuh jebakan. Paulo Freire mengingatkan, “Pendidikan sejati adalah praksis: refleksi dan aksi yang mengubah dunia.” Kampus yang mematikan daya kritis berarti sedang memadamkan api peradaban. Memberi ruang bagi suara yang berbeda adalah pupuk bagi akal sehat.
Maka, kepada para mahasiswa baru yang sebentar lagi menginjakkan kaki di gerbang kampus: jangan hanya menjadi penonton dalam panggung sejarah. Jangan puas menjadi penampung informasi; jadilah pengolah gagasan. Temukan ruang untuk mengasah logika, menajamkan empati, dan melatih kepemimpinan. Bergabunglah dengan organisasi, susunlah rencana, jatuhlah dan bangkitlah. Jadikan masa kuliah bukan sekadar transit, tapi perjalanan penuh cahaya. Sebab dunia tidak menunggu ijazahmu—dunia menunggu obor di tanganmu.
Penulis:
Fazar Rifqi As Sidik, M.Pd
Mantan Aktivis Kampus kini bertransformasi sebagai Dosen Muda di UIN Sunan Gunung Djati Bandung & STIT Az Zahra Tasikmalaya








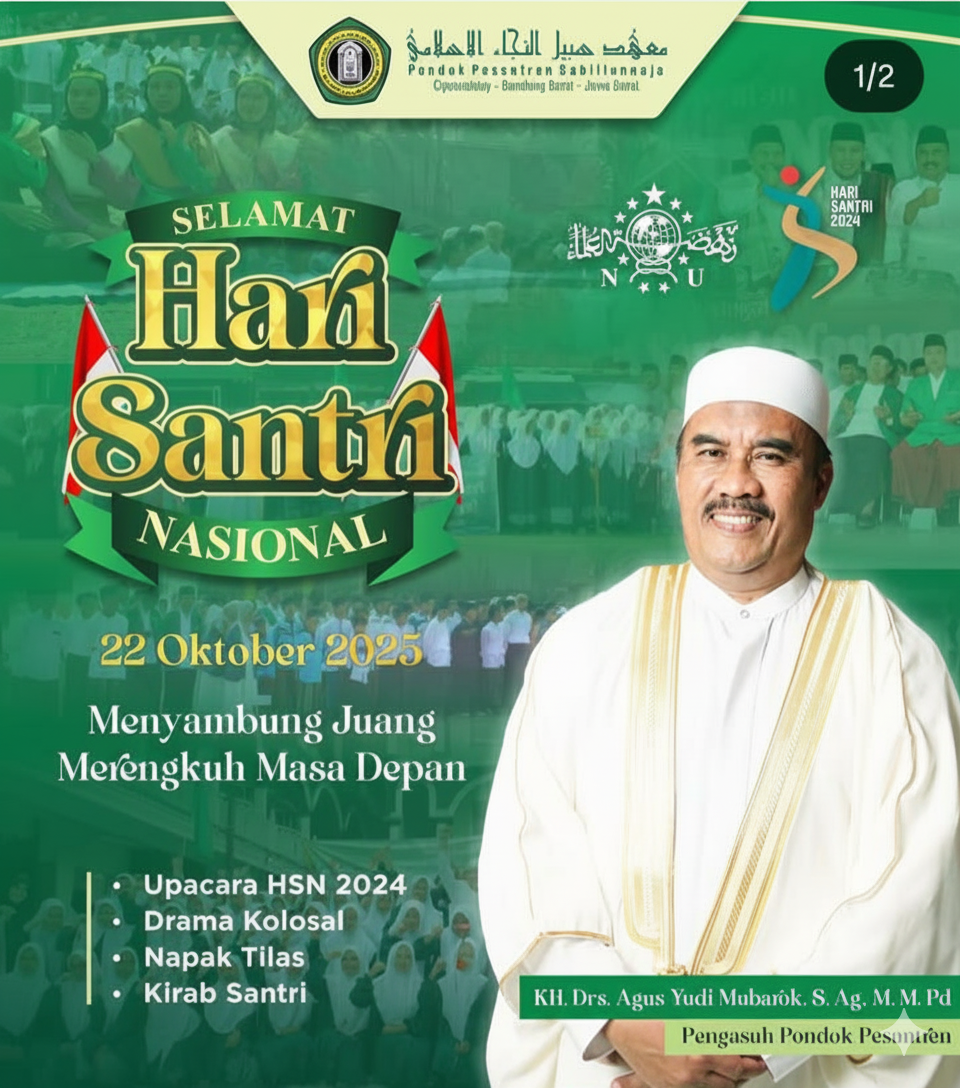

















1 Komentar