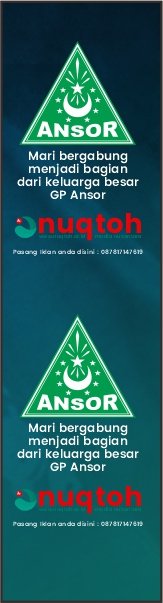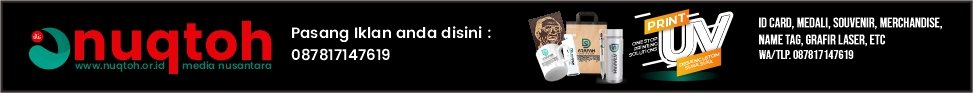Pendidikan adalah pondasi sebuah bangsa, namun belakangan saya terkejut menyaksikan bagaimana amanat pengalokasian dua puluh persen anggaran pendidikan dari APBN seringkali terseret ke ranah yang tumpang tindih, tidak selalu berpihak kepada mereka yang paling membutuhkannya. Ada sekolah kedinasan seperti IPDN, STAN, dan beberapa institusi afiliasi kementerian yang kuliah dan tinggalnya dijamin dari ujung kaki hingga ujung kepala. Para taruna dan mahasiswa di sana sudah memiliki gaji bulanan, fasilitas lengkap, dan setelah lulus dijamin seratus persen menjadi ASN. Sementara itu, banyak sekolah negeri dan terlebih lagi swasta—yang jumlahnya jauh lebih banyak—justru menangis di sudut-sudut kampung karena operasional, kesejahteraan guru, dan fasilitas pendidikan yang sangat terbatas.
Betulkah amanat dua puluh persen APBN itu benar-benar sampai ke mereka yang paling berhak? Data resmi menunjukkan bahwa untuk APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, atau setara dua puluh persen dari total belanja negara. Angka ini bahkan direncanakan naik menjadi Rp757,8 triliun pada 2026. Namun jika dirinci, dana tersebut terbagi lagi untuk berbagai pos seperti Bantuan Operasional Sekolah, tunjangan guru, KIP Kuliah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembiayaan abadi. Dari jumlah tersebut, pemerintah memang mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk gaji dan kesejahteraan guru dan dosen. Tapi ironisnya, survei IDEAS tahun 2024 memperlihatkan bahwa tujuh puluh empat persen guru honorer dan kontrak di Indonesia masih menerima gaji di bawah dua juta rupiah per bulan, bahkan sebagian di bawah lima ratus ribu rupiah.
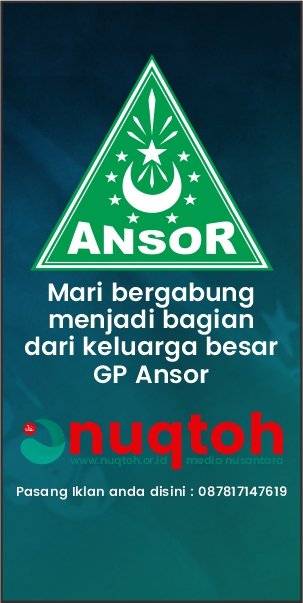
Contoh nyata bisa kita lihat di Jawa Barat. Di Bandung Barat, guru honorer kategori R2 dan R3 menerima insentif hanya Rp1,5 juta per tahun, atau sekitar seratus dua puluh lima ribu rupiah per bulan. Angka yang bahkan tidak cukup untuk ongkos transportasi mereka mengajar. Di Cirebon, ada SMK swasta di mana gaji guru hanya sekitar tiga ratus ribu rupiah per bulan, meski banyak dari mereka lulusan S1. Sementara kebijakan pemerintah provinsi menaikkan kapasitas rombongan belajar di SMA/SMK negeri dari 36 menjadi 50 siswa justru membuat ribuan sekolah swasta terjerembab karena kekurangan murid baru. Kondisi ini membuat kontribusi sekolah swasta, yang sejatinya menopang kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kian tersisih dan seakan berjalan sendirian.
Jika kita menengok ke negara lain, ironi ini semakin terasa. Vietnam, yang baru merdeka beberapa dekade setelah Indonesia, justru sudah mampu menaikkan kesejahteraan guru hingga tujuh puluh persen. Pada Oktober 2024, gaji guru di Vietnam bisa mencapai hingga VND30 juta per bulan atau sekitar 1.200 dolar AS setelah kenaikan gaji. Bahkan mulai 2026, pemerintah Vietnam akan menempatkan posisi gaji guru sebagai yang tertinggi dalam struktur karier administratif. Artinya kesadaran akan pentingnya pendidikan benar-benar dijadikan pondasi pembangunan. Bandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana banyak guru honorer masih harus berjuang dengan penghasilan di bawah garis layak, sementara beban hidup kian meroket.
Kondisi ini semakin mempertegas bahwa negara harus menata ulang orientasi pendidikan. Pendidikan tidak boleh dijadikan lahan basah yang di atas kertas tampak subur, namun di tataran rumput terasa kering. Sejatinya negara menjamin akses pendidikan tanpa pandang bulu bagi seluruh warganya, bukan hanya untuk mereka yang duduk di institusi kedinasan dengan segala privilese. Kritik ini bukanlah sekadar keluh kesah, melainkan bagian dari evaluasi yang harus terus dilakukan. Tadarus anggaran mesti segera dilakukan secara simultan, agar generasi mendatang tidak menjadi korban dari pengelolaan yang keliru.
Sebagaimana ditegaskan oleh Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar tidak meninggalkan kodrat hidup anak-anak kita. Tanpa orientasi finansial yang adil, cita-cita luhur itu akan terhenti di jalan. Negara sejatinya berdiri di atas lima pilar: ideologi yang kuat, struktur yang rapi, kultur yang terjaga, figur yang visioner, dan finansial yang kokoh. Dalam sektor pendidikan, aspek finansial menjadi syarat utama agar program dapat direalisasikan. Karena itu saya menyerukan agar para pemangku kebijakan melakukan terobosan nyata. Transparansi alokasi anggaran perlu diperketat, kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas, fasilitas berlebihan di lembaga kedinasan mesti dievaluasi, dan kampus swasta di daerah terpencil wajib mendapat dukungan operasional yang layak. Kita sudah menyumbang lewat pajak, kini giliran negara menjawab tanggung jawab konstitusionalnya.
Pendidikan bukan sekadar soal angka dan laporan, melainkan soal keadilan dan harapan. Mari kita suarakan keresahan ini bersama-sama, agar bangsa ini tidak berjalan di tempat. Karena bila generasi berikutnya dikorbankan, maka sejatinya kita sedang menggali lubang bagi masa depan negeri sendiri.
Penulis: Dr. (C) Fazar Rifqi As Sidik, M.Pd. (Dosen Muda Manajemen Pendidikan Islam UIN SGD Bandung & STIT Az Zahra Tasikmalaya, Awardee Doktoral LPDP Beasiswa Indonesia Bangit 2025, Founder Lembaga Psikotes Bidik Potensi, Penggagas ruang kajian Garasi Diskusi, Direktur CV 724)