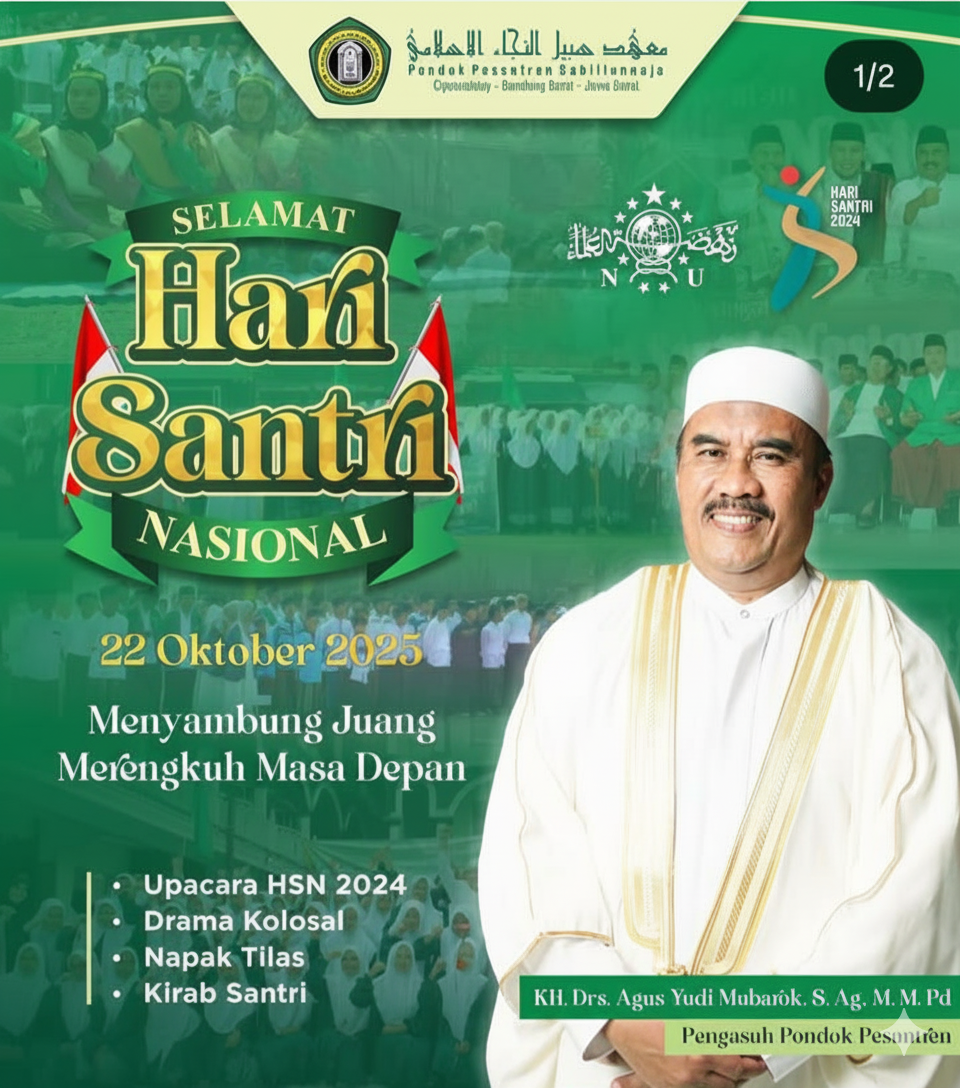Photo Istimewa Fazar Rifqi As Sidik, M.Pd
Hari ini, Senin, 1 September 2025. Seharusnya kelas-kelas di kampus negeri, PTKIN, dan segenap universitas membuka tirai pertemuan pertama. Ruang kuliah semestinya riuh oleh suara riang mahasiswa baru—yang masih wangi kertas fotokopian dan seragam OSPEK. Saya, sebagai dosen, biasanya akan berdiri dengan rasa semangat yang tak kalah riuh. Ada romantisme tersendiri di pertemuan pertama. Namun, apa daya, layar kaca kembali jadi panggung.
Ya, surat edaran datang seperti hujan deras di awal musim. “Perkuliahan daring mulai 1–6 September 2025.” Alasan klasik: eskalasi aksi massa. Beberapa hari lalu, jalanan mendidih oleh demonstrasi. Hari ini, seruan aksi masih berseliweran di jagat media. Beberapa sekolah dasar sampai madrasah aliyah memilih menutup pintu kelas, beralih ke daring, sekadar untuk meredam potensi chaos. Kita pun kembali ke layar. Lagi.

Saya menyesalkan ini. Sebab ruang kelas adalah panggung drama kehidupan yang tak tergantikan oleh Zoom. Pertemuan pertama bukan sekadar absen dan kontrak kuliah—ia adalah momen yang menyulut api semangat. Kata John Dewey, pendidikan bukan persiapan hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Dan hidup, sayang sekali, tidak terjadi di ruang maya berbingkai kotak-kotak.
Bayangkan, di pertemuan pertama itu biasanya kita menemukan keindahan-keindahan kecil yang absurd. Ada mahasiswa baru yang datang dengan wajah polos dan semangat yang nyaris suci. Ada juga yang sok dewasa, mematut diri bak aktivis senior, padahal seminggu lalu masih minta izin ke guru BK. Di pojok ruangan, ada yang melirik lawan jenis sambil menunduk pura-pura baca handout. Ada yang pemalu, menempel di tembok, takut jadi pusat perhatian. Ada pula yang percaya dirinya sudah superhero kampus—bicara lantang, menunjukkan tajinya, mengutip teori yang bahkan saya lupa siapa pengarangnya.
Pertemuan pertama juga adalah ajang show off performance yang paling manusiawi. Yang dulunya ketua OSIS tampil percaya diri, yang biasa pidato di masjid berusaha menyisipkan doa di sesi perkenalan. Ini bukan toxic, ini proses—sebab, menurut teori impression management ala Erving Goffman, manusia memang suka tampil dengan topeng-topeng sosialnya. Pertemuan pertama adalah panggung sandiwara sosial itu.
Lalu ada ritual sakral: pemilihan kosma dan PJ mata kuliah. Demokrasi mulai ditiupkan peluitnya. Ada yang mengangkat tangan sendiri tanpa diminta (ambisius detected), ada yang saling tunjuk teman, ada pula yang berusaha kabur ke toilet. Saya selalu menikmati itu, sebab di situlah cikal bakal dinamika besar: kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas diuji dalam versi mini. Kalau kata pewayangan, ini adalah kawah candradimuka—tempat tempaan para ksatria sebelum turun ke medan laga.
Sayangnya, semua itu sirna karena kita memilih Zoom alih-alih ziarah ke kampus. Interaksi cair berganti jadi suara delay. Canda tawa berubah jadi ikon emoji. Energi pertemuan pertama yang seharusnya liar dan hangat, kini dijinakkan oleh sinyal internet.
Saya tidak anti-daring. Tapi mari jujur, daring tidak pernah punya aroma yang sama dengan coretan spidol, ac tidak dingin , dan kursi citos yang mulai goyang. Daring adalah antitesis dari pertemuan pertama yang penuh geliat kehidupan.
Mungkin ini risiko hidup di zaman yang penuh turbulensi. Tapi saya tetap percaya, sekuat-kuatnya kebijakan, tidak ada algoritma yang bisa menggantikan tatap muka antara dosen dan mahasiswa di kelas pertama. Sebab dari tatapan itulah lahir cerita, persahabatan, dan chemistry yang kuat.
Penulis: Fazar Rifqi As Sidik, M.Pd (Mahasiswa Doktoral yang menyamar menjadi Dosen di UIN SGD Bandung)